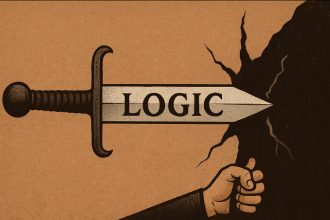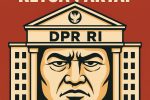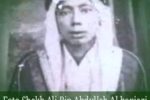Penulis:
Saidil Ambia | *Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah
Dari Yunani hingga Indonesia, filsafat membentuk cara berpikir dan upaya manusia mencari kebenaran. Menjadi dasar nilai, moral, dan ilmu modern.
KoranAceh.id | Kolom – Kalau kita lihat dunia hari ini dari cara orang berpikir, membuat keputusan, sampai bagaimana masyarakat membangun sistem nilai, semuanya ternyata punya jejak panjang yang berakar pada satu hal: filsafat. Filsafat bukan cuma urusan para pemikir tua yang merenung sambil menatap langit, tapi justru dasar dari hampir semua perkembangan ilmu dan cara pandang manusia modern.
Perjalanan filsafat sendiri punya cerita panjang yang seru, mulai dari Yunani kuno sampai akhirnya tumbuh dan beradaptasi di Indonesia. Dari sana, kita bisa melihat bagaimana ide dan pemikiran berkembang mengikuti perubahan zaman, tapi tetap punya satu tujuan: mencari kebenaran dan makna hidup.
Filsafat bermula dari dunia Barat, tepatnya di Yunani pada abad ke-6 SM ketika manusia mulai meninggalkan mitos dan mencari penjelasan rasional tentang alam. Tokoh seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles menjadi pelopor dan membuka jalan baru dalam cara berpikir manusia. Mereka tidak hanya sekadar bertanya “apa yang terjadi”, tapi juga “mengapa” dan “bagaimana seharusnya kita hidup”.
Socrates menekankan introspeksi melalui prinsip “kenali dirimu sendiri.” Plato mengembangkan konsep dunia ide, sementara Aristoteles menekankan logika dan observasi. Dari gagasan mereka, lahirlah dasar ilmu pengetahuan modern.
Pada abad ke-8 hingga ke-13, dunia Islam mengambil alih tongkat estafet intelektual. Karya-karya Yunani diterjemahkan dan dikembangkan oleh pemikir seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Mereka tidak hanya mengadopsi gagasan Yunani, tetapi menyesuaikannya dengan ajaran Islam.
Ibnu Sina, misalnya, berhasil memadukan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia percaya bahwa akal dan wahyu bukan dua hal yang bertentangan, tapi saling melengkapi. “Ilmu adalah kesempurnaan jiwa manusia yang tertinggi,” kata Ibnu Sina. Dari sinilah terlihat bahwa filsafat dalam Islam bukan hanya soal logika, tapi juga soal spiritualitas memahami Tuhan dan ciptaan-Nya dengan cara berpikir yang mendalam.
Memasuki masa renaisans, Eropa menghidupkan kembali semangat berpikir rasional. Descartes dengan “Cogito ergo sum” melahirkan rasionalisme dan menjadi cikal bakal lahirnya rasionalisme hingga akhirnya menjadi dasar ilmu pengetahuan modern seperti yang kini kita kenal. Kendati begitu, kemajuan tersebut turut memunculkan kegelisahan baru. Banyak filsuf abad ke-20 seperti Jean-Paul Sartre dan Friedrich Nietzsche mempertanyakan makna hidup dalam dunia yang makin rasional namun kehilangan kedalaman. Dari sinilah lahir pemikiran eksistensialisme bahwa manusia harus menemukan maknanya sendiri di dunia yang terus berubah.
Di Nusantara, pemikiran filosofis telah hidup jauh sebelum istilah “filsafat” diperkenalkan. Nilai gotong royong, musyawarah, dan adat adalah cermin pandangan hidup yang menekankan keseimbangan dan kemanusiaan. Setelah masa kolonial, pemikir seperti Soekarno, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Notonagoro membangun filsafat yang berakar pada budaya Indonesia. Notonagoro, misalnya, menempatkan Pancasila sebagai filsafat moral, budaya, dan ketuhanan yang menyatukan dimensi rasional dan spiritual.
Dari Yunani kuno hingga Indonesia, filsafat adalah perjalanan panjang manusia mencari kebenaran. Setiap zaman dan setiap bangsa berkontribusi melalui gagasan masing-masing. Filsafat mengajarkan pentingnya berpikir kritis sekaligus kerendahan hati. Seperti pengakuan Socrates bahwa ia tidak tahu apa-apa, pencarian kebenaran selalu berawal dari kesediaan untuk terus belajar.