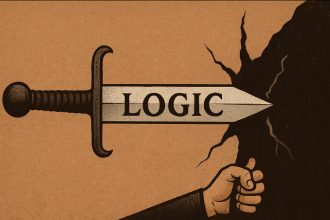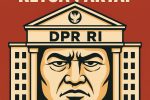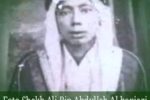Penulis:
Zulfa Dilla
Negara menabalkan korban dan penguasa di altar yang sama. Rekonsiliasi antara palu dan kepala yang dipukul.
KoranAceh.id | Kolom — Hari ini, tanggal 10 November yang merupakan Hari Pahlawan, bangsa Indonesia kembali memberi penghormatan kepada para tokoh yang dianggap berjasa melalui pengukuhan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh nama. Pelaksanaan pengukuhan gelar tersebut dilaksanakan di Istana negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Di antara mereka, dua sosok langsung menarik perhatian publik, yaitu Soeharto dan Marsinah.
Keduanya sama-sama bagian penting dari sejarah Indonesia, namun berada di dua kutub yang sangat berbeda. Soeharto adalah presiden yang berkuasa selama 32 tahun, pemimpin Orde Baru yang identik dengan stabilitas sekaligus represi. Sementara Marsinah adalah buruh pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, yang disiksa hingga tewas karena menuntut keadilan bagi rekan-rekannya pada Mei 1993.
Bahwa kedua nama ini diabadikan dalam satu upacara pengukuhan yang sama menimbulkan perasaan ganjil: seolah negara sedang memuliakan korban dan pelaku dari sistem yang sama, pada saat yang sama.
Marsinah: Buruh yang Tak Pernah Diam
Awal Mei 1993, para buruh PT Catur Putra Surya menuntut agar perusahaan menerapkan upah minimum sesuai keputusan gubernur, yakni Rp1.750 per hari. Manajemen menolak dan tetap membayar Rp1.500. Aksi mogok pun terjadi. Namun alih-alih berdialog, pihak perusahaan justru memanggil aparat militer untuk “menyelesaikan” masalah.
Sebanyak 13 buruh dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Marsinah, yang menolak pemaksaan itu, menulis surat protes dan menuntut keadilan. Beberapa hari kemudian, ia menghilang. Tiga hari setelahnya, jasadnya ditemukan di Nganjuk, penuh luka penyiksaan.
Hingga kini, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Marsinah tidak pernah diungkap. Namun namanya menjadi simbol perjuangan buruh dan keberanian perempuan menghadapi ketidakadilan negara dan korporasi.
Soeharto: Pembangunan yang Menyisakan Luka
Soeharto sering dijuluki “Bapak Pembangunan” karena keberhasilannya menstabilkan ekonomi dan membangun infrastruktur yang mendorong modernisasi Indonesia. Di bawah pemerintahannya, kota-kota berkembang, jalan-jalan terbangun, dan pertumbuhan ekonomi terlihat gemilang di permukaan. Citra ini membuat banyak orang menilai pemerintahannya sebagai era pembangunan yang sukses.
Namun, di balik narasi itu tersimpan sejarah gelap yang tak bisa diabaikan. Pembantaian 1965–1966, tragedi Tanjung Priok, insiden Talangsari, hingga pembungkaman pers dan penindasan terhadap aktivis menunjukkan bahwa pembangunan itu menelan harga mahal bagi rakyat. Nyawa, kebebasan, dan keadilan dibayar dengan penderitaan yang mendalam. Sejarah Soeharto adalah pengingat bahwa kemajuan materi tidak selalu sejalan dengan keadilan dan kemanusiaan.
Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional: Antara Jasa dan Luka
Ungkapan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait alasan Soeharto dikukuhkan menjadi pahlawan Indonesia “Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.” (Komparatif.id, November 2025)
Politisi senior Partai Golkar yang juga anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo berpendapat bahwa Presiden Soeharto bukan hanya sosok pemimpin yang tegas dan berwibawa, tetapi juga figur pembangunan yang berhasil membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan stabilitas nasional di masa pemerintahannya. Karena itu, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menjadi sesuatu yang layak dan penuh makna. (rakyat menilai, November 2025)
Akan Tetapi Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan bahwa pemberian gelar kehormatan tak seharusnya hanya menilai kontribusi pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak moral seseorang terhadap warganya. Mengabaikan sisi gelap kekuasaan berarti menghapus sebagian kebenaran sejarah itu sendiri (NU Online, Oktober 2025).
Kontradiksi Simbolik
Pengukuhan Soeharto dan Marsinah pada hari yang sama bukan hanya kebetulan administratif, melainkan paradoks simbolik. Marsinah adalah korban dari sistem represif Orde Baru, sedangkan Soeharto adalah arsitek sistem tersebut. Pengukuhan ini merupakan bentuk dari “rekonsiliasi semu”
Rekonsiliasi semu merupakan proses atau upaya perdamaian yang tampak seperti rekonsiliasi (memperbaiki hubungan), tetapi sebenarnya tidak menyentuh akar persoalan atau keadilan substantif. Dengan kata lain, itu adalah “rekonsiliasi palsu” tampak damai di permukaan, namun tidak benar-benar menyembuhkan luka sosial, politik, atau moral yang mendasarinya.
Pahlawan, Keadilan, dan Ingatan
Gelar pahlawan sejatinya bukan hanya penghargaan terhadap jasa, tetapi juga pernyataan moral negara tentang apa yang dianggap benar. Ketika korban dan penguasa disetarakan tanpa konteks, penghargaan kehilangan makna etisnya.
Pemberian gelar kepada Soeharto mungkin dimaksudkan sebagai pengakuan atas jasanya dalam pembangunan. Namun di saat bersamaan, pengukuhan Marsinah mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh meniadakan keadilan dan kemanusiaan. Ia adalah simbol dari keberanian warga kecil melawan kekuasaan besar.
Menutup Luka, Bukan Menghapus Ingatan
Bangsa yang besar tidak hanya mengenang jasa, tapi juga berani menghadapi sejarah dengan jujur. Mungkin, dengan mengingat Marsinah, kita tidak sekadar mengenang seorang buruh, tetapi juga belajar tentang harga yang dibayar rakyat kecil agar kata “keadilan” memiliki makna nyata. Sementara dengan mengingat Soeharto, kita diingatkan bahwa kekuasaan, betapapun besar jasanya, harus tetap tunduk pada nurani kemanusiaan.
Menyamakan keduanya dalam satu perayaan tanpa refleksi justru berisiko menenggelamkan pesan paling penting dari sejarah itu sendiri, bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang berkuasa, melainkan mereka yang berani berkata benar di tengah ketakutan. []