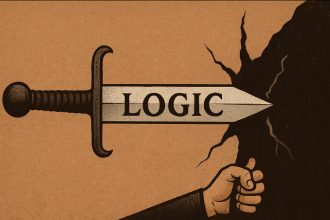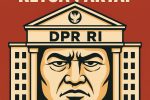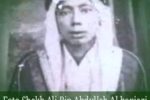Aceh merespons ucapan Benny dengan mengingat kembali kontribusi sejarahnya. Pertemuan Mualem–Prabowo membawa tambahan anggaran yang membuka ruang harapan.
KoranAceh.id | Kolom – Pada Jumat sore, 14 November 2025, setelah menandatangani KUA–PPAS 2026 bersama DPRA, Mualem berdiri di depan para anggota dewan dan pejabat Forkopimda.
Ia tersenyum. Senyum yang jarang ia tunjukkan di forum formal. Lalu ia berkata: “Tadi malam Pak Prabowo menambah uang untuk Aceh 2026 sebanyak delapan triliun. Bagaimana, puas?”
Ruangan itu langsung riuh. Beberapa anggota dewan bertepuk tangan. Sebagian lain saling menatap, tidak percaya. Tambahan Rp8 triliun adalah jumlah yang tidak kecil. Ini adalah napas baru bagi APBA. Sebuah peluang untuk memperbaiki apa yang hancur pelan-pelan selama bertahun-tahun. Tidak berhenti di sana. Mualem melanjutkan: “Dan dikasih dana hibah dua triliun untuk mantan kombatan.”
Pernyataan itu membuat suasana semakin ramai. Bagi sebagian orang, dana hibah ini bukan hanya anggaran—ia adalah pengakuan politik, janji lama yang belum selesai ditepati oleh negara pasca-Helsinki.
Pertemuan Tiga Jam yang Menentukan
Pada Kamis malam, 13 November 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, duduk berhadap-hadapan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan itu berlangsung tiga jam, sebuah durasi yang tidak biasa untuk seorang kepala daerah. Ini menandakan bahwa pembicaraan itu bukan basa-basi.
Di dalam ruangan, Mualem memaparkan satu per satu masalah Aceh: kebutuhan mendesak Jalan Sawang, proyek infrastruktur yang macet, penanganan banjir, sekolah-sekolah SMK yang kekurangan fasilitas, pembangunan rumah sakit regional, proyek Kuala Idi dan program Aceh Hebat yang terhenti karena anggaran
Semuanya disampaikan dengan nada lugas, khas Mualem. Tidak ada basa-basi. Tidak ada penghalusan. Mualem datang bukan sebagai peminta-minta. Ia datang sebagai kepala daerah yang membawa suara rakyatnya. Dan Prabowo, menurut Mualem, mendengarkan.
Luka yang Dibangunkan oleh Sebuah Kalimat
Sementara siang Jum’at itu juga, video berdurasi kurang dari satu menit itu beredar begitu cepat di linimasa orang Aceh. Wajah Benny Kabul Harman muncul dengan ekspresi datar, tetapi kalimatnya menghentak—bagi sebagian orang bahkan menusuk.
“Aceh jangan sampai ketergantungan pusat…” katanya dalam RDPU revisi UUPA. Nada bicaranya seperti teguran, tetapi bagi banyak orang Aceh terasa seperti tamparan yang mengingatkan luka yang belum kering.
Reaksi publik Aceh tak sekadar emosional; ia datang dari ruang-ruang memori yang pernah menyimpan perang, keterbatasan, kehilangan, dan perasaan diabaikan oleh negara. Setiap kali ada yang meremehkan Aceh, mereka merasa seolah sejarah mereka dipelintir di depan mata.
Karena Aceh bukan provinsi yang pernah hidup dari belas kasihan. Aceh pernah berdiri sebagai tiang pertama Republik. Dan itulah yang dilupakan oleh Benny.
Aceh Pernah Menopang Republik, Bukan Sebaliknya
Tidak banyak politisi generasi sekarang yang betul-betul memahami betapa besar kontribusi Aceh pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada 1945, ketika Indonesia baru berdiri dan dunia belum mengakui kedaulatannya, Aceh justru tampil sebagai penyangga negara muda.
Para saudagar Aceh, dipimpin tokoh-tokoh niaga di Kutaraja—tanpa perintah, tanpa desakan, tanpa imbalan—mengumpulkan dana besar dan membeli dua pesawat terbang pertama Republik Indonesia: RI-001 Seulawah dan RI-002.
Pesawat itu bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol bahwa Aceh melihat Indonesia sebagai rumah perjuangan bersama.
Lantas, bagaimana mungkin hari ini Aceh dituding akan “bergantung” pada pusat? Banyak orang Aceh merasa ucapan Benny menghapus bab penting sejarah itu. Padahal sejarah itu bukan hanya kebanggaan; ia adalah utang moral negara kepada Aceh.
Jalan Panjang Menuju Keterpurukan
Yang lebih ironis, setelah bergabung dengan Republik, ekonomi Aceh perlahan-lahan bukannya meningkat, tetapi justru merosot.
Dalam kurun beberapa dekade, Aceh mengalami: sentralisasi kekuasaan, eksploitasi sumber daya tanpa pemerataan, konflik bersenjata sepanjang puluhan tahun, operasi militer yang menghancurkan struktur sosial, minimnya investasi jangka panjang dan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah
Konflik yang berkobar sejak masa DI/TII, hingga puncaknya perang Aceh 1976–2005, memutus rantai kemajuan. Ratusan ribu orang mengalami trauma mendalam. Perekonomian macet. Infrastruktur terbengkalai. Anak-anak tumbuh dewasa tidak dengan mimpi, tetapi dengan ketakutan.
Dan ketika tsunami 2004 datang seperti malaikat maut, Aceh bukan hanya kehilangan ribuan warganya. Ia kehilangan struktur ekonomi, kehilangan rumah, kehilangan arah.
Hari ini, menurut rilis terbaru BPS, Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatra, dengan tingkat pengangguran yang berada di atas rata-rata pulau Sumatera.
Mendengar semua ini, Aceh bertanya: “Ketergantungan apa yang dimaksud Benny?”
Luka Aceh Adalah Luka yang Hidup
Ketika orang luar berbicara tentang Aceh, mereka sering lupa bahwa provinsi ini bukan sekadar angka statistik atau obyek kebijakan pusat. Aceh adalah ruang hidup dari jutaan manusia yang masih membawa bekas-bekas sejarah di tubuh mereka.
Cukup satu kalimat meremehkan, maka memori itu hadir lagi. Luka Aceh bukan hanya berasal dari masa konflik atau tsunami. Luka itu datang dari pengalaman panjang tidak diakui, tidak dihargai, dan tidak dimengerti.
Karena itu, ucapan Benny terasa tidak menghormati perjalanan panjang Aceh menuju damai.Di media sosial, komentar bernada getir bermunculan: “Kalau bukan karena Aceh, republik ini mungkin tidak punya sayap.”
“Bicaralah dengan data, bukan dengan prasangka.” “Bukan kami yang bergantung. Tapi negara yang berkewajiban menepati janji.” Namun di tengah riuh kritik dan kekecewaan itu, sebuah kabar baik datang dari Jakarta.
Aceh Tidak Pernah Menuntut Lebih dari Haknya
Dalam politik, jarang ada momentum yang merangkum emosi publik, narasi sejarah, dan realitas ekonomi dalam satu episode. Polemik Benny dan hasil pertemuan Mualem–Prabowo adalah salah satunya.
Ucapan Benny yang menyederhanakan Aceh sebagai provinsi “berpotensi bergantung” terasa kosong ketika dihadapkan pada fakta sejarah yang panjang.
Dan keputusan Prabowo memberi tambahan Rp8 triliun justru membuktikan bahwa Aceh bukan meminta belas kasihan. Aceh hanya meminta negara kembali mengingat janjinya.
Janji untuk membangun infrastruktur pasca-perdamaian. Janji untuk memulihkan ekonomi. Janji untuk memperbaiki luka-luka masa konflik. Janji untuk menepati MoU Helsinki secara penuh. Janji untuk memperlakukan Aceh bukan sebagai halaman belakang, tetapi sebagai bagian terhormat dari NKRI.
Ketika Luka, Harga Diri, dan Harapan Berjalan Bersama
Aceh memang tidak seperti daerah lain. Ingatan kolektifnya panjang, traumanya dalam, tetapi harga dirinya tinggi.
Masyarakat Aceh bisa menerima kritik mengenai tata kelola Otsus, mengenai kebijakan daerah, mengenai pemimpin mereka sendiri.
Namun mereka tidak bisa menerima ketika harga diri sejarah mereka diremehkan oleh siapa pun.
Ucapan Benny menyentuh titik sensitif itu. Dan karenanya publik merespons bukan dengan analisis dingin, tetapi dengan nurani.
Tapi dalam keberisikan itu, kabar tambahan dana Rp10 triliun (Rp8 triliun + Rp2 triliun hibah) seperti membuka jendela harapan baru bagi Aceh.
Mualem pulang membawa angin segar. Prabowo memberi sinyal positif. Dan Aceh menemukan kembali ruang untuk berharap.
Aceh Tidak Pernah Bergantung — Aceh Mengingat
Dalam perjalanan panjang bangsa ini, Aceh bukan penumpang. Aceh adalah salah satu pengemudi pertama yang membantu menjalankan Republik ketika negara ini bahkan tidak punya roda.
Yang diinginkan Aceh hari ini bukan pujian, bukan belas kasihan, dan bukan propaganda politik.
Yang diinginkan Aceh adalah pengakuan yang jujur: bahwa Aceh pernah memberi terlalu banyak, dan sekarang Aceh hanya ingin apa yang menjadi haknya.
Tambahan dana dari Prabowo adalah langkah penting. Tapi menghormati sejarah Aceh adalah langkah yang jauh lebih besar.
Karena Aceh memiliki satu kalimat yang tidak pernah berubah sejak berabad-abad lalu: “Kami berdiri di mana kami dihargai.” []