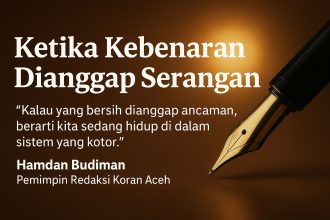Akankah kekayaan alam ini benar-benar menyejahterakan rakyat Aceh? Ataukah kita hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri, sementara hasil bumi terus mengalir keluar tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan yang nyata?
KoranAceh.id — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf—yang lebih dikenal dengan nama Mualem, bukan hanya seorang kepala daerah. Ia adalah simbol dari perjalanan panjang Aceh: dari masa perjuangan bersenjata, menuju babak baru pemerintahan yang damai dan berdaulat di bawah bingkai Republik Indonesia.
Sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kini Mualem berdiri di panggung diplomasi, menyambut tamu-tamu penting dunia dengan tangan terbuka dan hati yang penuh tekad untuk membawa Aceh ke arah yang lebih bermartabat.
Dalam beberapa bulan terakhir, pendopo Gubernur Aceh dan Bandara Sultan Iskandar Muda menjadi saksi dari serangkaian kunjungan diplomatik yang jarang terjadi dalam intensitas seperti ini.
Duta Besar Kerajaan Maroko, Amerika Serikat, Jordania, Bahrain, Bangladesh, Turki, Inggris, Uni Eropa, hingga Rusia — semuanya datang ke Aceh.
Mereka datang bukan sekadar membawa salam diplomasi, tetapi juga sinyal bahwa Aceh kembali diperhitungkan dalam peta geopolitik dan ekonomi dunia.
Diplomasi yang Berakar dari Sejarah: Antara Potensi dan Janji
Bagi rakyat Aceh, diplomasi bukan hal baru. Sejak abad ke-16, Aceh sudah menjadi poros pertemuan dunia. Di masa Kesultanan Aceh Darussalam, para utusan dari Turki Utsmani, Gujarat, hingga Maroko kerap berlabuh di pelabuhan Kutaraja — bukan sekadar berdagang, tetapi menjalin aliansi dalam semangat Islam dan peradaban.
Kini, berabad-abad kemudian, sejarah itu seakan berulang dalam bentuk yang baru: Aceh kembali menjadi ruang pertemuan antarbangsa. Namun kali ini, bukan dengan meriam dan rempah, melainkan dengan investasi, energi, dan nilai kemanusiaan.
Setiap duta besar yang datang melihat hal yang sama: Aceh adalah tanah yang kaya — bukan hanya pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada semangat manusianya.
Sejak ditemukannya gas alam di Arun, Lhokseumawe pada tahun 1976, hingga penemuan baru di perairan Laut Andaman yang disebut-sebut sebagai salah satu cadangan gas terbesar di dunia, Aceh selalu menjadi magnet bagi kepentingan global.
Di darat, emas, bijih besi, batubara, dan hasil bumi lainnya masih tersimpan di bawah tanah yang belum sepenuhnya tergali. Di laut, sumber daya perikanan dan energi baru terbarukan menunggu disentuh dengan kebijakan yang bijak.
Dan di atasnya, terbentang panorama alam dari Sabang hingga Laut Tawar, yang menawarkan pesona wisata berkelas dunia. Namun di balik semua kekayaan itu, pertanyaan mendasar masih bergema:
Akankah kekayaan alam ini benar-benar menyejahterakan rakyat Aceh? Ataukah kita hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri, sementara hasil bumi terus mengalir keluar tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan yang nyata?
Isu MoU Helsinki dan Diplomasi Kemanusiaan: Harapan dari Serambi Mekkah
Dalam pertemuan dengan para duta besar, Mualem juga mengangkat satu isu penting yang menjadi dasar kedamaian Aceh: MoU Helsinki. Perjanjian yang menandai akhir konflik panjang itu belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya.
Ada pasal-pasal yang tertunda, ada komitmen yang belum tuntas, dan ada harapan rakyat yang masih menggantung. Pembahasan tentang perdamaian dan pembangunan berkeadilan menjadi tema yang tak terelakkan dalam setiap dialog diplomatik.
Mualem tampak memahami bahwa diplomasi tidak hanya berbicara tentang investasi, tetapi juga tentang pengakuan terhadap hak dan martabat rakyat Aceh.
Aceh kembali berada di persimpangan sejarah. Kedatangan para duta besar ini bisa menjadi angin perubahan, jika diikuti dengan kerja konkret dan kemauan politik yang sungguh-sungguh.
Kerja sama ekonomi dan kemanusiaan harus menjadi jembatan, bukan sekadar seremoni. Kekayaan alam harus dikelola dengan kedaulatan rakyat, bukan hanya keuntungan investor.
Mualem kini berada pada posisi yang unik — antara sejarah dan masa depan. Ia adalah saksi dari perjuangan yang getir, sekaligus pemimpin yang diharapkan menuntun rakyat menuju kesejahteraan yang dijanjikan.
Dan seperti kata pepatah Aceh lama:
“Lam wat jaroe that keu ubat, lam pih mate that keu raseuki.”
(Dalam tangan ada obat, dalam tanah ada rezeki.)
Artinya, semua kebaikan telah tersedia di bumi Aceh ini — tinggal bagaimana ia dikelola dengan niat dan amanah. Aceh telah melalui perang dan perdamaian, kehilangan dan kebangkitan.
Kini, dengan kedatangan para duta besar dunia, pintu baru telah terbuka. Namun, yang menentukan ke mana langkah ini akan berlabuh bukanlah para tamu itu, melainkan kebijakan, integritas, dan keberanian kita sendiri.
Semoga diplomasi yang kini dibangun dari Serambi Mekkah tidak hanya memperkuat hubungan antarnegara, tetapi juga menghidupkan harapan rakyat Aceh — bahwa kedamaian bukan hanya berhenti di atas kertas, melainkan tumbuh nyata dalam kesejahteraan dan keadilan di bumi yang diberkahi ini. []